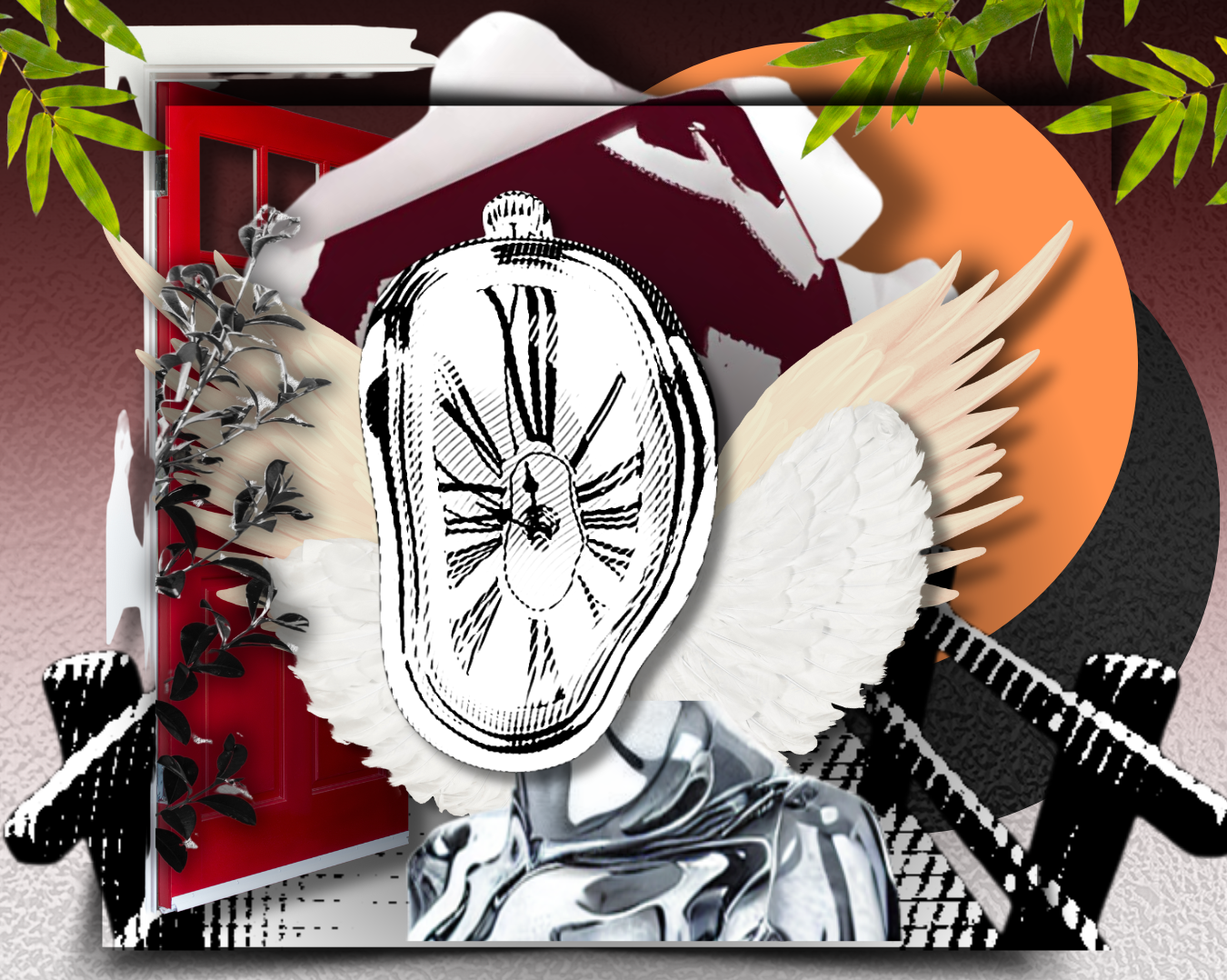Oleh: Aufa Niamillah
Bapak meninggal satu bulan yang lalu karena kecelakaan di jalan oleh motor ugal-ugalan. Lalu entah bagaimana, Ibu juga tiba-tiba jatuh sakit. Kurasa sakit yang Ibu derita cukup parah, karena hingga hari ini ia hampir tidak pernah bangun dari tempat tidur. Badannya kian lemah dan ekspresinya makin pucat saja setiap harinya, membuatku takut untuk sekadar melihat wajahnya.
Sementara itu Abang, satu-satunya saudara laki-lakiku, biasanya meninggalkan rumah dengan seragam putih abu-abu di pagi hari. Ia pergi ke sekolah. Bapak dahulu pernah berkata, bahwa orang yang sekolah tinggi bisa menjadi orang sukses di masa depan. Makanya, meski kesulitan dan tidak punya banyak uang, kami harus pergi sekolah. Namun, semua berbeda sejak Bapak mati. Abang tidak pernah pergi sekolah lagi. Aku jadi sering bertanya, apakah ia bisa menjadi orang sukses nantinya?
Kemudian aku menyadari makanan di meja makan berkurang setiap harinya. Tidak ada lagi tahu goreng kesukaanku, hanya ada tempe dan saus. Terkadang ada semangkuk bayam yang hanya cukup untuk dua porsi, tapi tidak lagi sesering dulu ketika Bapak masih hidup. Sedikit yang aku tahu, sepertinya keuangan kami memburuk. Malam itu, setelah mencuci piring makan malamku, aku mencari Abang. Ia tidak ada di kamarnya, jadi aku pergi mencarinya ke halaman depan. Ketika itu, bulan begitu bulat dan ia bersinar terang-terangnya di langit gelap. Cahaya terpantul ke tanah dan jalanan.
“Abang,” aku mendapati Abang duduk sendiri dalam diam.
Aku memanggilnya sekali lagi hingga ia menoleh dan tersenyum, “Ada apa?”
“Abang sedang apa?”
“Berdoa.”
“Tapi kita tidak sedang di masjid?”
Abang terkekeh, “Tidak perlu pergi ke masjid untuk berdoa. Apa kamu tahu? Tuhan Maha Mendengar. Kita bisa berdoa dimanapun kita mau, dan Ia mendengarkan.”
Aku menganggukkan kepala kemudian, “Abang berdoa untuk siapa?”
Ia tak menjawab dan aku segera tahu ia tak berdoa untuk siapapun. Ia mendongakkan kepala, menatap bulan yang berpendar di langit dengan tatapan kosong. Aku menyadari bagaimana lingkaran di bawah matanya menghitam kelelahan. Ia pastilah sudah mencari dan mencoba berbagai macam pekerjaan demi sesuap nasi yang baru saja kumakan. Aku belum pernah melihat Abang seperti ini sebelumnya, ia selalu dipenuhi energi dan terlihat cerah seperti matahari.
Kupeluk lutut, merenung di sampingnya sebelum kudengar ia berujar.
“Aku sedang berdoa pada Tuhan agar kita bisa bertahan hidup.”
Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar darinya sebelum ia beranjak masuk ke dalam rumah, kemudian mengunci dirinya di kamar selama tujuh hari. Aku hanya bisa menerka-nerka. Mungkin ia sedang bermeditasi.
***
Pada hari ketujuh, Abang keluar dari kamar. Aku melihatnya, nyaris takjub, sebab tubuhnya berkilau bak tembaga. Ia hanya mengenakan celana yang panjangnya selutut. Ia tersenyum lebar kepadaku, giginya yang biasanya kuning terlihat lebih putih. Abang berputar, seperti menari. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia dilapisi warna perak. Hanya matanya yang masih terlihat putih. Aku tidak tahu bagaimana ia melakukannya tapi batinku ingin berteriak, cantik!
Aku baru akan bertanya perihal apa yang terjadi selama tujuh hari belakangan ketika ia sampai di pintu depan. Pertanyaanku tertahan, Abang nampak sangat bahagia.
“Aku pergi dulu, kau tunggu di rumah dan kerjakan PR,” ujarnya.
“Sungguh? Bang, sepertinya aku tidak perlu pergi ke sekolah.”
“Jangan. Cukup aku saja yang berhenti sekolah. Abang janji akan membayar semua biaya pendidikanmu,” Abang terkekeh, “Tolong jaga Ibu sementara aku pergi mencari uang. Dah!”
Jujur saja, aku belum pernah melihat Abang tersenyum begitu lebar sejak Bapak pergi. Setiap hari Abang berangkat dengan semangat yang berkilau, sementara aku merawat ibu di rumah. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan keadaan ekonomi kami membaik. Di meja makan, selalu ada tahu goreng tepung kesukaanku, serta sup hangat. Kadang-kadang Abang membawa ikan gurame atau lele, bahkan ayam goreng. Hanya ibu yang tidak pernah membaik.
Rasanya seperti mimpi. Kami hidup dalam kesulitan sejak waktu yang tak bisa kuingat lagi. Kami adalah keluarga miskin yang menganggap uang adalah barang langka. Namun, sejak Abang menjadi manusia perak, kami tak pernah kekurangan lagi. Aku bahkan bisa membeli sepatu baru. Biaya sekolahku selalu dibayar tepat waktu, tak pernah terlambat lagi.
Pernah pada suatu kali, Abang pulang lebih awal dengan tampilan yang cukup mengkhawatirkan. Rambutnya yang biasanya sudah tidak rapi makin acak-acakan, satu lututnya lecet dan berdarah. Aku khawatir dia mengalami hal buruk, tapi Abang tersenyum seperti biasa.
“Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Abangmu tidak akan mati hari ini,” Abang tertawa sambil membersihkan lukanya dengan handuk basah.
Seiring berjalannya waktu, aku bisa melihat bahwa Abang mencintai pekerjaannya. Setiap hari dia pergi meninggalkan rumah dengan penuh kilauan perak yang sama. Selama itu, aku tak pernah bertanya dari mana asal kilauan itu, atau apa yang terjadi saat dia mengurung diri di kamar selama tujuh hari.
Selama kami hidup dengan lebih baik, apa lagi yang bisa aku minta?
Aku bahagia dengan kehidupan kami. Aku senang melihat lesung pipit di pipi Abang setiap kali dia tersenyum. Aku bahagia hari ini meskipun ibu kami tak bisa bertahan dan meninggal dunia saat aku di SMA kelas menengah—yah, dia selalu terbaring di tempat tidur, tak ada yang benar-benar berubah setelah dia meninggal. Aku masih punya Abang. Abang merawatku dengan baik, dia memberikan segalanya untukku.
Abang selalu mengatakan bahwa aku harus menyelesaikan studiku hingga perguruan tinggi, setidaknya sampai mendapatkan gelar sarjana. Dia mengulang kata-kata Bapak seperti lagu yang diputar di radio setiap hari.
“Ingat, jika kamu ingin menjadi orang sukses, kamu harus menempuh pendidikan tinggi. Sudahkah kamu memikirkan jurusan yang kamu minati? Bagaimana dengan beasiswa? Ada banyak beasiswa yang bisa kamu pilih,” setelah itu Abang mencari informasi tentang beasiswa.
Aku hanya menganggukkan kepala karena aku tahu pilihan Abang lebih baik dari apapun. Kemudian, aku mengikuti ujian masuk universitas swasta melalui jalur beasiswa. Aku belum pernah menceritakan ini sebelumnya, tapi aku pernah mengikuti berbagai kompetisi saat SMA yang beruntungnya membawaku meraih banyak kemenangan. Nilai-nilaiku pun selalu baik di kelas. Meski sedikit khawatir tak bisa melakukannya, Abang selalu ada di sisiku, mengatakan bahwa dia sudah berdoa, semuanya akan baik-baik saja. Aku pun menjadi cukup tenang.
Dua bulan setelah ujian beasiswa dan sebulan sebelum kelulusan, aku menerima pengumuman hasil ujian beasiswa melalui email. Aku berhasil. Aku lulus. Itu adalah pencapaian besar yang dirayakan Abang dengan membelikanku makanan lezat di restoran. Saat itu, aku merasa hidupku sempurna. Hingga suatu pagi setelah kelulusanku, Abang mendekatiku. Dia menepuk pundakku, menatapku dengan bangga.
“Aku sangat bangga padamu. Setelah ini, aku ingin berhenti bekerja, bagaimana menurutmu?”
“Apa… kenapa berhenti? Aku suka melihatmu bekerja. Apakah kau tidak menyukai pekerjaanmu?”
Abang hanya tertawa, seolah tertawa pada pertanyaan lucu yang keluar dari mulut bayi.
“Hei, kamu harus belajar dengan baik. Jadi, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada aku,” kata Abang.
“Hm … ya, tentu saja.”
Abang benar-benar berhenti menjadi manusia perak dan membuka toko kecil di depan rumah kami yang masih sama sejak Bapak meninggal. Rumah kami tak banyak berubah, yang berubah adalah halaman yang dulu tandus, kini dipenuhi berbagai tanaman hijau. Abang menanamnya dua tahun lalu. Sekarang toko kecilnya dibuka dengan sedikit uang dari tabungan Abang. Sejak toko kecil itu dikelola, banyak tetangga datang membeli kebutuhan mereka, atau anak-anak yang ingin membeli camilan kesukaan mereka.
Terkadang aku masih membayangkan Abang dan kilau peraknya.
**
Semuanya berjalan lancar, begitu baik. Tapi hidup kami yang telah membaik tiba-tiba hancur ketika Abang jatuh sakit di tahun ketiga kuliahku. Aku merasa sakit yang diderita Abang sangat aneh. Dia tidak sakit seperti ibu, atau seperti tipes yang pernah kualami beberapa tahun lalu. Awalnya dia terlihat seperti demam biasa, masih bisa berjalan ke dapur untuk makan, mengurus toko kecilnya, dan masih menungguku pulang di ruang tamu. Namun seiring waktu, dia terlihat sangat sakit. Kulit Abang kering, sangat kering. Tubuhnya seperti menyusut hari demi hari.
Aku duduk di sampingnya di tepi kasur, saat itu tanggal tiga puluh September. Abang tampak begitu pucat, matanya muram, aku tak bisa menemukan tatapan cerah yang selalu Abang berikan padaku sebelum dia sakit. Tapi kali itu, Abang membuka matanya, menatapku gamang, dalam. Rasanya aku bisa tersedot ke dalamnya kapanpun. Aku mencoba memberikan senyuman terbaikku, meskipun sangat sulit.
“Bang, bagaimana perasaanmu hari ini?” aku memperhatikan kulitnya yang membalut tulang, hampir tak ada daging.
Abang hanya menjawab dengan garis tipis di bibirnya.
“Hei … jangan ikuti jalanku. Kau harus mencari pekerjaan yang baik dan benar, serta menghasilkan banyak uang. Jangan ikuti jalanku. Selalu perhatikan kesehatanmu, jaga dirimu saat aku tidak ada nanti. Aku sangat menyayangimu, kamu tahu itu, kan?” kata Abang, suaranya sedikit gemetar, “Jangan ikuti jalanku …”
Ya, aku tahu, aku tahu itu dengan baik. Jangan berkata seperti itu seolah-olah kau akan pergi seperti Ibu dan Bapak, tetaplah di sini….
“Janji padaku, kamu akan hidup lebih baik. Janji padaku.”
“Aku janji padamu.”
Aku menganggukkan kepala, tanganku menggenggam tangannya yang hangat, tapi sangat kering. Kasar. Tak lama kemudian, setelah Abang seolah memastikan bahwa aku baik-baik saja, napasnya mulai tak beraturan. Dia menatap langit-langit, tangan yang masih kugenggam terasa mati rasa. Abang tak bergerak lagi. Dia telah pergi. Kutatap wajah yang selalu menyambutku pulang, lalu tangannya, lalu kakinya, semua kulit keringnya. Aku tidak mengerti… Aku menunduk, merasakan air mata perlahan mengalir di pipiku. Dadaku sesak, sangat sakit. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Berat, aku menangis semakin keras.
Wajah Abang yang tersenyum lebar dengan kilau perak di kulitnya terbayang dalam benakku kembali.
***
Seorang polisi dengan tampang lebih tampan membolak-balik berkas latar belakang salah satu tahanan jalanan yang baru saja mereka tangkap. Dahinya berkerut. Kemudian temannya yang agak gemuk datang menghampirinya, meletakkan borgol di atas meja. Dia melirik berkas yang dibaca si Tampan.
“Ah, tahanan itu …, bukankah aneh? Dia bersekolah hingga sarjana, tapi berakhir di jalanan seperti itu. Padahal nilai dan rekam jejaknya sangat bagus. Dia bisa menjadi karyawan dengan gaji tinggi.”
Si Tampan mengerutkan dahi, “Kenapa dia memilih bekerja sebagai manusia perak?”
Si Gemuk mendesah, memilih untuk berbisik sebelum menjawab, “Aku baru saja selesai bertanya padanya. Jawabannya sangat aneh. Dia bilang … pekerjaan ini sakral. Tuhan memberkatinya jika dia melakukan pekerjaan ini, hidupnya jauh lebih baik setelah Abangnya menjadi manusia perak. Dia ingin melanjutkan pekerjaan ini agar tidak dikutuk. Abangnya, meninggal dengan cara yang aneh. Menurutnya Tuhan marah karena Abangnya berhenti bekerja sebagai manusia perak suci.”
“Tunggu apa—omong kosong! Bukankah dia meninggal seperti itu karena infeksi dari campuran cat perak?”
Si Gemuk mengangkat bahu dan berjalan pergi. Si Tampan menoleh kembali ke dalam, mengintip sedikit ke sel sementara. Di sana, seorang pria dengan tubuh dilapisi cat perak dan celana pendek krem, setengah telanjang duduk bersila di lantai. Lututnya lecet sebelah karena terjatuh ketika dikejar polisi. Matanya menatap dinding di seberang. Dia tampak begitu tenang, seperti seorang suci yang baru saja menerima wahyu dari Tuhannya.
****
Grafis: Dhiya Najah Fitria