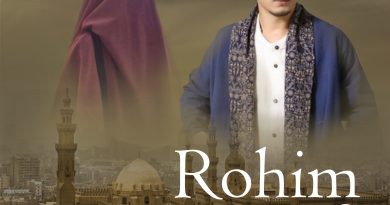Cerita tak Terlihat
Meja-meja di sekitar kami mulai sepi. Piring-piring dan gelas sisa pengunjung malam ini perlahan dibawa menuju ke dapur di bagian belakang Café. Menyisakan kami berdua yang dikelilingi meja kosong dengan bangku yang disusun rapi di atas meja. Suara air mengalir dan suara perkakas makan yang sedang dicuci, mengisi kesunyian meja kami yang hanya diam sejak satu jam sebelumnya. Sesekali aku meminum sedikit demi sedikit Café Latte yang semakin dingin. Sedangkan, dia hanya memandang jauh ke jendela Café tanpa bersuara sedikit pun. Hanya memandang.
Hingar bingar kota terlukis dengan jelas di jendela Café. Di matanya, cahaya lampu kota dari kejauhan terpantul dan mengukir siluet-siluet di garis wajahnya. Dia selalu suka tempat ini. Café kecil di atas bukit dengan pemandangan kota dari kejauhan, dan selalu duduk di tempat yang sama. Di meja kecil dekat jendela, di ujung pojok kiri Café. Entah berapa ratus jam telah ia habiskan hanya untuk duduk dan memandang jendela itu. Aku yakin, dia mungkin telah hafal jumlah debu di jendela itu.
“Manda,” katanya, memecahkan keheningan di antara kami berdua tanpa memalingkan muka dari jendela Café.
“Ya?” jawabku sambil memandang wajahnya yang sedang termenung.
“Kamu ingat setahun yang lalu, ketika kita pertama kali bertemu disini?” kali ini, matanya bergulir menatap mataku sekilas lalu berbalik kembali memandang jendela.
“Iya. Aku ingat, dan kita hanya duduk diam saja disini. Sama seperti sekarang.”
“Dan waktu itu kamu bertanya, kenapa aku selalu memandang jendela ini? Aku rasa aku sudah tahu jawabannya,” ia membenarkan tempat duduknya dan kini matanya yang tajam namun teduh, memandangku dengan serius.
“Jadi, kenapa?”
“Coba, kamu perhatikan cahaya-cahaya itu,” tangannya menunjuk ke cahaya-cahaya redup kota.
“Oke. Itu kan cuman cahaya dari lampu mobil di jalan, dan beberapa mungkin cahaya dari rumah-rumah, gedung apartemen, dan lain-lain. Semua kota punya itu, Rian.”
“Nggak cuman itu, Manda,” ia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum.
“Cahaya-cahaya itu nggak begitu saja ada. Kamu tau kan pasti ada orang yang nyalain?” lanjutnya.
“Dan di setiap orang-orang yang nggak kita kenal itu. Mereka itu ada, hidup dengan cerita rumit yang mereka miliki—setiap orang tak dikenal itu, punya ambisi, teman, rutinitas, dan kecemasan. Cerita-cerita besar tak terlihat itu, begitu saja bergerak di sekitarmu. Seperti terowongan-terowongan dengan pintu-pintu menuju ribuan terowongan lain yang kamu nggak pernah tau pernah ada.”
“Dan di setiap ribuan cerita tak terlihat itu. Aku dan kamu, juga pernah jadi bagian dari cerita itu walau hanya sekilas?” tanyaku.
“Iya, dan kita pernah jadi bagian kecil dari cerita itu. Mungkin sebagai suara seruputan kopi dan adukan sendok di Café. Mungkin, sebagai remang-remang lampu lalu lintas di jalan raya. Atau, mungkin sebagai jendela terang di tengah fajar.”
Kami berdua kembali terdiam. Matanya memandang jauh ke langit-langit Café, seakan matanya sedang menerawang menembus susunan beton dan menatap langit malam. Sedangkan aku, mengetuk-ngetukan jariku ke meja dan menyandungkan nada-nada acak.
“Pernah nggak kamu berpikir,” tanyanya.
“Mungkin, di kejauhan sana. Di salah satu dari ribuan cahaya redup itu. Seseorang sedang memikirkan hal yang sama seperti kita.”
“Ya,” jawabku. “Dan mungkin, saat ini ia sedang berpikir kalau di salah satu lampu dari ribuan remang-remang lampu di atas bukit. Mungkin ada sebuah Café yang hampir tutup. Di Café tersebut, sedang ada sepasang orang yang baru saja memutuskan hubungannya,” kataku sembari mengaduk-ngaduk gelasku yang telah kosong.
“Lalu mereka berdua hanya duduk. Diam saja tanpa sepatah kata. Dan entah kenapa, mereka justru senang dengan itu,” lanjutku.
“Mungkin orang itu lalu berpikir, ‘Dan aku disini, tak akan pernah tahu tentang cerita tak terlihat itu. Tak akan pernah tahu kenapa mereka begitu senang duduk berdiam-diam di Café sambil memandang cahaya-cahaya kota yang redup. Membayangkan ribuan cerita tak terlihat yang tidak akan pernah mereka dengar’.” (*Rizky Eka Satya)
*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 2015
Ilustrasi: Magang Kognisia/Raufan Gusrananda